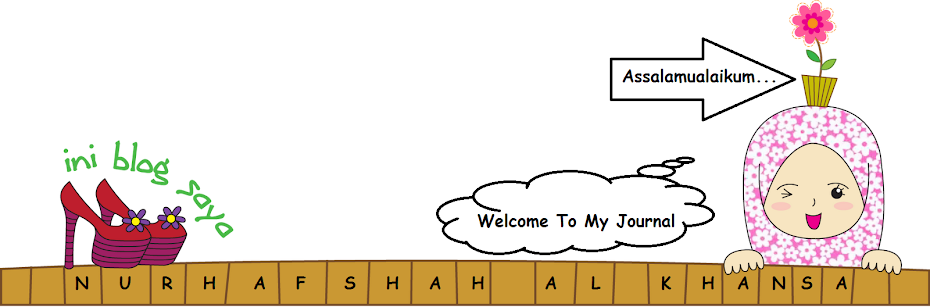Niat lulus cepet biar cepet dapet kerja ternyata gak semulus
yang direncanakan. Dulu, aku maksa Tuhan banget biar bisa lulus bulan Mei 2017.
Tapi justru bermula dari paksaan itu lah ujian terberatnya. Adalah ketika kita
sulit mencari alasan untuk bersyukur. Pada akhirnya, satu per satu keluhan
mulai datang hingga menumpuk-numpuk di pikiran. Aku mendustakan nikmat Tuhan
atas anugerah-Nya diberi kesempatan memakai toga lebih dulu dibanding
teman-teman. Meskipun sebenarnya banyak sekali pengalaman, pelajaran, nikmat,
ujian kesabaran dan tantangan yang aku dapat selama pencarian kerja ini. Meruginya,
itu semua tidak juga mampu mendobrak hati untuk sekedar mengucap
“Alhamdulillah”.
Maka mulai detik ini, setiap kali aku menginginkan sesuatu
bahkan menginginkan seseorang, aku jera untuk memaksa Tuhan. Sekarang aku lebih
suka memakai kalimat “Berikan yang terbaik, seseorang yang terbaik, di waktu
yang terbaik”. Aku tidak akan mengatur-atur Tuhan lagi, karena bisa jadi Tuhan
mengabulkan tapi dengan kemurkaan. Karena aku terlalu memaksa dan mengatur
dalam berdoa, bisa jadi Tuhan justru memberi dengan cara melempar. Jika seperti
itu, mana bisa aku meraih makna keberkahan; yang ada hanya keluhan dan
kekufuran.
Tiga tahun lalu, aku sempat memaksa Tuhan agar bisa bekerja
di Badan Ekonomi Kreatif. Tapi aku melupakan itu sampai pada suatu hari ketika aku mau mendaftar
CPNS, tidak sengaja “kepencet” memilih Instansi Bekraf. Sungguh, ini benar-benar
ketidaksengajaan karena aku berniat mendaftar di Instansi lain. Sejak kejadian
janggal itu, aku mulai kepedean dengan Tuhan. Aku berfikir Tuhan ingin memberi kejutan
untuk mengabulkan doaku tiga tahun lalu.
Aku terus belajar dengan keras, belajar lewat simulasi CAT yang disediakan BKN. Disana
setiap satu kali ujian ada 100 soal berbeda tentang Wawasan Kebangsaan,
Intelegensia Umum dan Kepribadian. Terhitung aku melahap, memahami, mencatat
sekaligus menghafal sebanyak 10x tes simulasi berarti setara dengan 1000 soal
latihan. Tidak hanya itu, aku juga belajar dari Buku Panduan Tentang Soal CPNS.
Pernah suatu hari ketika kepala terasa amat penat, aku
menangis dan melempar buku catatanku. Aku menangis karena merasa rapuh dan
berat mengingat aku harus bersaing dengan 12.000 orang. Untuk membayangkannya
saja berasa ingin muntah. Tapi seketika aku sadar dan meminta maaf kepada buku
catatan yang aku lempar. Bagaimana pun juga di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Lalu
aku memotivasi diri bahwa dengan Tuhan membuatku berada di jalur menuju
perjalanan ini, artinya semakin dekat aku dengan terkabulnya doa.
Ringkas cerita, aku ikut tes CPNS di Aula Hotel Bumi Kitri
Bandung bersama ibu dan paman. Kami tiba 3 jam lebih awal. Waktu tes tiba,
sungguh merasa sia-sia karena soal-soal dan materi yang aku pelajari tidak satu
pun keluar. Tapi aku tetap mencoba mengerjakan 100 soal tersebut dengan cepat
dan teliti dalam waktu 90 menit. Sampai tiba sisa waktu satu menit, aku sudah
yakin dengan semua jawaban. Lalu aku klik “selesai” dan Alhamdulillah, di luar
dugaan nilaiku di atas Passing Grade yaitu 339 (TWK: 75, TIU: 105, dan TKP:
159).
Aku bahagia luar biasa. Aku berfikir Tuhan betul-betul tidak
mengecewakan doaku. Lalu kami pulang ke Bogor dengan suka cita. Sampai tiba
hari pengumuman selanjutnya, hatiku sangat terpukul dan kecewa karena yang
berhak ikut ke tahap selanjutnya (Psikotes dan Kesehatan) adalah 8 orang dengan
nilai tertinggi. Aku dan 157 orang lainnya tersaring seperti butiran debu yang
tidak berarti.
Pelajarannya bukan pada gagalnya. Tapi maukah kita mengambil
hikmah? Karena pada posisi terjepit itulah Tuhan ingin kita membuktikan bahwa
kita harus Ridho dengan segala ketentuan-Nya. Selalu ada, akan selalu ada,
pasti ada, alasan untuk kita bersyukur. Yaitu dari ribuan orang yang ikut tes,
seharusnya aku bersyukur bisa masuk 165 besar yang nilainya memenuhi walaupun
tidak ikut tahap berikutnya. Tapi lagi-lagi, aku gagal mencari celah untuk
bersyukur.
Aku sibuk patah hati kepada Tuhan. Aku merasa kecewa berat,
bahkan hidup seperti sangat menyesakkan dada. Semua seperti menghimpit, kecil
dan tidak berguna. Benang merahnya ialah bukan tidak boleh berharap penuh
kepada Tuhan. Tapi sikap merendah dan pasrah di depan Tuhan itu yang paling
penting. Selama ini, Tuhan tidak pernah sama sekali atau sekali pun
mengecewakanku. Tapi satu kali Tuhan tidak mengabulkan keinginan, aku bisa
begitu marah luar biasa. Sungguh, aku sangat malu dengan sikap angkuh yang
demikian.
Maka Tuhan, dengan segala kerendahan diri ini, aku memohon
ampun dan maafmu. Maaf atas segala keangkuhan yang tidak berhak. Maaf untuk
kemarahan yang tidak semestinya. Untuk setiap detak dan detik yang Engkau beri,
sungguh kuatkanlah hati ini agar tetap beriman. Tetap mencintai-Mu seburuk
apapun keadaanku, seberat apapun ujian yang menimpa. Tuhan, jangan biarkan aku
salah memahami-Mu. Sungguh berikan segala kebaikan dan pengertian kepadaku
bahwa setiap nafas hidup dan matiku hanya untuk-Mu.
Bogor, 14 November 2017